Berita
Penegakan Keadilan dan HAM: Mimpi Jauh di Awang-Awang
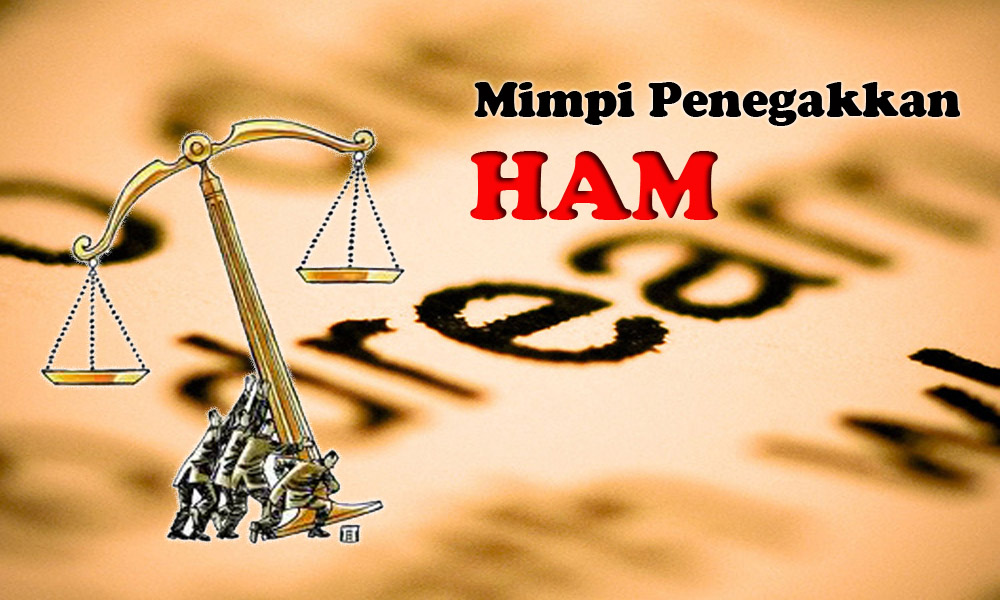
Apakah dengan bergantinya rezim berganti pula penegakan hukum dan keadilan, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Apakah harapan ini bisa kita rasakan di masa sekarang? Sayang sekali, sepertinya semua itu masih jauh panggang dari api. Penegakan keadilan masih menjadi mimpi.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Al Ghifari Aqsa yang menengarai pemerintahan Jokowi masih abai terhadap keadilan dan HAM.
“Penguasa dengan sangat mudah membuat regulasi dalam bisnis. Dalam hitungan hari bisa berubah dengan sangat cepat. Tapi untuk bikin regulasi keadilan dan HAM begitu sulit,” ujar Aqsa.
“Pemerintah mau merevisi dan konsolidasikan 42 ribu peraturan di tahun 2016 harus dikurangi sampai setengahnya, jadi 21 ribu regulasi saja. Tapi itu untuk kepentingan bisnis dan melanggengkan proyek-proyek ekonomi Jokowi-JK.”
“Tapi di sisi lain peraturan hukum dan kemanusiaan, mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi misalnya sampai sekarang juga belum disahkan. RUU mengenai penyandang disabilitas, perlindungan PRT, perlindungan kekerasan seksual, KUHAP yang lebih berperspektif korban, masih mandeg di DPR,” ujar Aqsa.
Hukum Lemah Pada Si Kaya, Kejam Pada Si Miskin
Selain ketidakberpihakan pada penegakan HAM, diskriminasi hukum pada si kaya dan si miskin juga terlihat jelas.
“Saya contohkan, bulan lalu warga kali Sekretaris 35 KK digusur di Jakarta Barat karena dianggap menempati RPH, di samping kali. Tapi di saat yang sama, warga Kemang, yang juga tinggal di pinggiran kali, oleh Ahok justru kalinya, bantarannya ditinggikan supaya gak masuk ke rumah warga.”
“Bayangkan, satu sisi masyarakat miskin digusur, tapi yang kaya ditingggiin temboknya. Dan itu pake dana APBD juga. Mall di Kemang itu di sisi kali juga. Berani gak Ahok gusur itu? Hukum kita masih diskriminatif dan bias. Itu yg terjadi,” keluh Aqsa.
Beberapa catatan lain adalah dari sisi perlindungan keadilan, Indonesia juga berada di urutan 52 dari 102 negara. Juga tak adanya sistem koreksi yang efektif untuk aparat di peradilan.
“Indonesia Hanya memiliki poin 0,1 untuk sistem koreksi yang efektif di peradilan. Artinya aparat kita tak bisa dikoreksi sama sekali. Jadi kalau mereka melanggar atau menindas gak bisa dikoreksi,” terang Aqsa.
“Seperti contoh ketika melakukan agresi ke buruh, kriminalisasi pada 49 aktivis anti korupsi siapa yang mengoreksi? Bahkan Komisi Yudisial justru dilemahkan. Ada gerakan penghapusan KY di UUD.”
“Bayangkan, Komisi Yudisial yang gunanya untuk menjaga check and balance lembaga peradilan mau dilemahkan,” tekan Aqsa.
Tak hanya ketidakadilan demi ketidakadilan, menurut Aqsa, pemerintah makin represif dengan diturunkannya tentara dalam penggusuran-penggusuran. Demikian juga ancaman terhadap pengacara makin keras.
“Bayangkan, aktivis 98 berhasil kembalikan tentara ke barak. Dihapusnya dwifungsi TNI/ABRI. Di UU 2004 dikatakan tentara hanya punya fungsi dalam hal pertahanan, kalau keamanan itu polisi. Ketertiban umum itu Satpol PP. Ini bayangkan, tentara dilibatkan di ketertiban umum. Ini menginjak-injak TNI.”
“Belum ancaman terhadap pengacara. Situasi makin represif. Dalam 1 bulan, tiga orang pekerja bantuan hukum LBH Jakarta ditangkap. Dua mendampingi aksi buruh, satu mendampingi aksi mahasiswa Papua. Ditangkap dan dipukuli,” kritik Aqsa.
“Tujuh kasus pelanggaran HAM masih di Kejagung, pengungkapan kebenaran atas tragedi 65 selalu dijegal, 423 Aksi Kamisan juga tak didengar. Kami melihat ada kemunduran dalam penegakan keadilan dan hukum,” ujar Aqsa.
Intoleransi Kian Tinggi
Satrio Wirataru, Staf Divisi Pembelaan Hak Sipil & Politik KontraS menyebutkan dalam soal intoleransi Indonesia masih bermasalah.
“Dalam riset Pew Research Institute tahun 2014 terhadap 198 negara, intensitas konflik berlatar agama berada pada peringkat 13. Sementara pada aturan dan regulasi yang membatasi kehidupan beragama meraih peringkat kedua,” ujar Satrio.
Satrio mengkritik pemerintahan Jokowi hanya sibuk dengan wacana saja.
“PR besar Jokowi adalah mengurusi banyaknya regulasi yang diskriminatif, baik aturan di tingkat Nasional maupun daerah. Seperti PNPs No. 1/1965 terkait penistaan agama, PBM 2 Menteri terkait mekanisme pendirian rumah ibadah, dan SKB 3 Menteri terkait Ahmadiyah. Juga ada puluhan aturan Perda bernuansa keagamaan yang berpotensi diskriminatif lainnya.”
“Tapi semua masih di level wacana saja. Kelompok masyarakat sipil itu harapannya udah tinggi. Dari wacana-wacana itu belum ada relevansinya yang signifikan. Sampai sekarang,” kritik Satrio.
Satrio juga menilai pemerintah tidak serius menegakkan keadilan dan HAM. Ia melihat pemerintah cenderung memahami upaya perlindungan HAM sebagai sesuatu yang transaksional.
“Pemerintah cenderung melihat perlindungan HAM itu secara ‘transaksional’, artinya perumusan kebijakan perlindungan HAM KBB juga harus tetap dengan mempertahankan kebijakan yang cenderung diskriminatif.”
“Ini seperti mengatakan, okelah hak-hak kalian kami lindungi. Tapi tetap jangan copot hak-hak kami untuk melanggar hak kalian. Kan gak nyambung,” ujar Satrio.
Menurut Satrio masyarakat sebaiknya tidak terkecoh dengan janji-janji perubahan kebijakan yang pada akhirnya berujung pada kebijakan diskriminatif yang baru.
“Lebih baik masyarakat sipil memfokuskan tenaganya kembali pada penyelesaian kasus diskriminasi dan mengedepankan cara yang lebih agresif, yakni melalui advokasi litigasi di lapangan,” saran Satrio.
“Selain itu, akan lebih tepat apabila advokasi isu toleransi beragama kepada Negara tidak lagi difokuskan kepada ‘figur’ negara di pucuk-pucuk pemerintahan, melainkan terhadap aparatur negara di tingkatan-tingkatan ‘pelaksana’ yang memang lebih dekat dengan pokok persoalan dan lebih jauh dari kepentingan-kepentingan transaksional,” tambahnya.
Pesimisme pemerintah mau mendengar suara rakyatnya dan menegakkan keadilan seharusnya tidak terjadi. Negara mestinya melindungi rakyatnya. Semoga ini tidak terus menjadi mimpi yang jauh di awang-awang. (Muhammad/Yudhi)

