Berita
Islam Politik Simpatik, Mungkinkah?
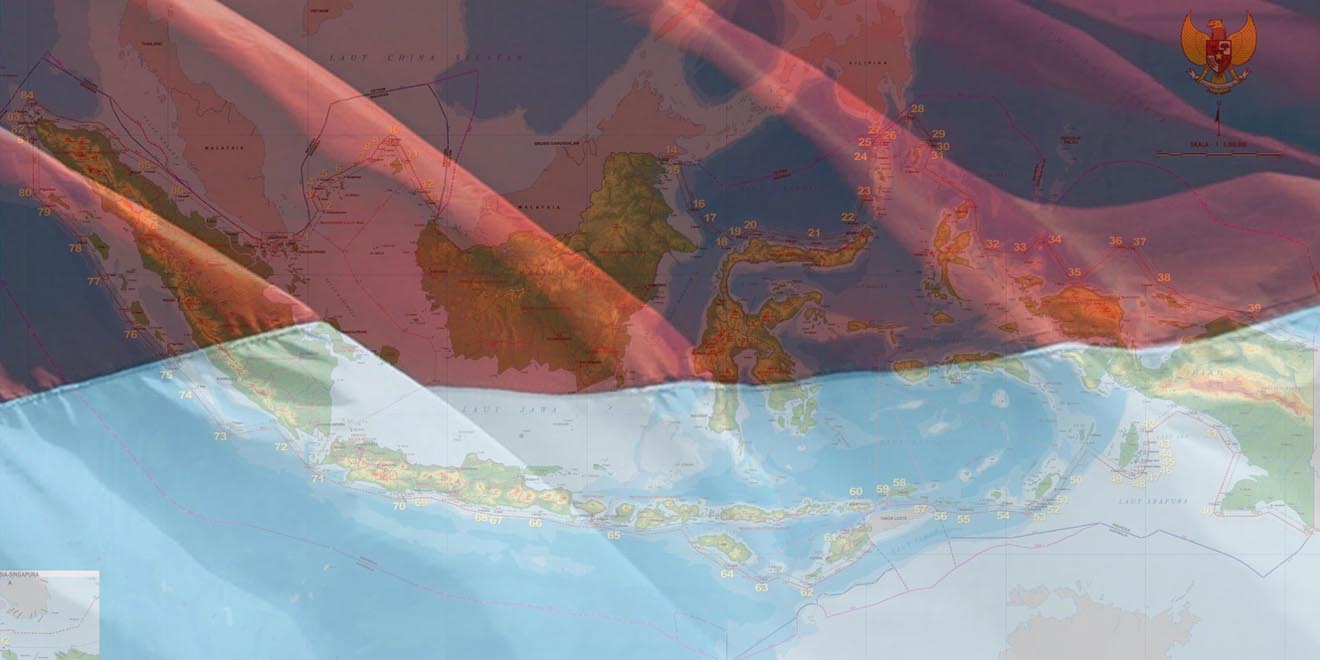
Membicarakan perkembangan iklim intelektual kampus memang tidak akan ada habisnya. Itulah mengapa sebagai mahasiswa saya mencoba untuk menikmati sisa waktu studi untuk menikmati dinamika iklim tersebut.
Teringat beberapa bulan menjelang pemilu 2014, seorang kawan non-muslim menawarkan kepada saya untuk ikut diskusi terbuka mengenai demokrasi di Indonesia yang dihelat oleh unit kerohanian fakultas. Saya mengiyakan tawaran itu dan segera bergabung dalam forum. Rupanya, mayoritas peserta adalah simpatisan dari salah satu ormas yang rajin mengkampanyekan khilafah sebagai sistem politik alternatif.
Argumen pro-kontra terhadap pelaksanaan demokrasi di Tanah Air berlangsung cukup hangat. Titik klimaks terjadi saat seorang simpatisan berpendapat bahwa demokrasi menyebabkan umat mayoritas menjadi kerdil di hadapan umat beragama minoritas. “Contoh di Bali, umat Islam dilarang sembelih sapi. Kita dipaksa tunduk dengan adat mereka! Seharusnya pemeluk agama lain sadar jika mereka jumlahnya kecil. Gara-gara demokrasi, kita sebagai mayoritas jadi kayak gini. Itulah kenapa kita harus memperjuangkan khilafah!” Kalimat ini tidak begitu mengagetkan karena kuping saya sudah kebal dengan dagangan macam begini, namun tidak bagi sang kawan, rautnya berubah marah. Menjelang berakhirnya forum, kawan ini mengungkap jati diri keyakinannya serta berapi-api mengutarakan pendapat jika sistem khilafah versi mereka jelas tidak mengayomi kebhinekaan.
Dipaparkan pula bagaimana pengalamannya di kampung halaman kala sekelompok orang yang mengatasnamakan penegakan sistem syariah menghancurkan rumah ibadahnya. Kontan saja forum terhenyak mendengar pengakuan tersebut. Wa bil khusus, sang simpatisan yang secara tak sadar terbongkar hidden agenda gerakannya di hadapan publik, jelas kebakaran jenggot. Buru-buru ia mengklarifikasi kepada kawan saya bahwa kisah pahit penghancuran rumah ibadah yang dialaminya itu hanyalah ulah “oknum,” tidak mencermikan Islam yang luhur, dan gerakan khilafahnya tidak akan berbuat intoleran jika berkuasa kelak. Namun apa lacur, sang simpatisan terlanjur membuka boroknya sendiri dengan penuh gairah.
Mari Membuka Sejarah
Peristiwa ini merupakan tamparan telak bagi siapapun yang masih ngotot mempertahankan penerapan ideologi Islam yang tak ramah terhadap keragaman dan cenderung sekadar rahmatan lil muslimin. Para pengusung khilafah maupun konsep Islam politik apapun bentuknya harus sadar bahwa mereka tidak hanya mengemban kepentingan kaum muslim, tapi seluruh kehidupan di dalamnya yang beraneka ragam, sejalan dengan misi kenabian (rahmatan lil alamin). Yang sering atau sengaja luput dari perhatian aktivis khilafah, seperti dalam cerita di atas, adalah aspek konteks sosial Indonesia. Sebab, seideal apapun sebuah ideologi atau sistem politik tetaplah harus mampu bersifat fleksibel sesuai kondisi objektif sebuah negara. Untuk urusan mensintesiskan sistem politik ideal normatif dengan fakta masyarakat yang dinamis, nampaknya gerakan khilafah yang memimpikan komunitas homogen harus belajar banyak dari pengalaman sejarah.
Kekhilafahan Turki Utsmani yang dijadikan sebagai role-model oleh ormas pendamba revivalisme Islam pernah melakukan kebijakan reformis pada tahun 1839-1876 yang lazim disebut sebagai Gerakan Tanzimat.[1] Beberapa kebijakan yang diambil oleh para Sultan selama periode Tanzimat ini terang-terangan mengadopsi beberapa konsep sekuler seperti mengenalkan sistem hukum Eropa ala Napoleon Bonaparte dan hukum adat di samping hukum syariah, pengakuan kesetaraan hak di hadapan hukum bagi non-muslim berdasarkan Dekrit Gulhane, serta menyatakan homoseksualitas bukan pelanggaran hukum. Apa pasal reformasi dilakukan? Menurut Ishtiaq Hussain dalam tulisannya mengenai ini, di pertengahan abad ke-18 khilafah Utsmani mulai menunjukkan kemunduran akibat perang, pemberontakan, tuntutan dari Eropa untuk menghargai hak minoritas beragama, dan kebutuhan untuk menyegarkan kembali sistem lama yang tidak sesuai perubahan zaman.
Pula, sebagai contoh kedua kita dapat belajar dari kearifan Imam Khomeini ketika merumuskan sistem politik Wilayah al-Faqih. Meski Iran mampu merealisasikan bentuk negara Republik Islam, namun Imam tidak memaksakan pemikiran politiknya (aql i’tibari) harus terwujud di negara-negara lain apalagi jika sampai mempersekusi pemeluk agama berbeda, dikarenakan Imam menyadari bahwa setiap nation-state tentulah memiliki akar historis dan kekayaan sosial-politik yang berbeda dari Iran.
Sepatutnya, sebelum menyesal seperti sang aktivis dalam cerita saya sebelumnya, ulasan ini bisa menjadi tempelengan yang lebih keras bagi ikhwan agar mau mendefinisikan ulang khilafah sesuai cita rasa Nusantara yang plural. Saya yakin bahwa politik Islam yang simpatik masih sangat mungkin hadir untuk diterima di bumi Indonesia jika ada kemauan dalam tubuh gerakan untuk melakukan otokritik dan kesediaan merangkul banyak kalangan. (Fikri/Yudhi)
[1] Hussain, Ishtiaq.2011.The Tanzimat: Secular Reforms in The Ottoman Empire. Faith Matters. (Paper Ilmiah versi Pdf).













