Pustaka
Jejak Dakwah Damai Habib di Indonesia
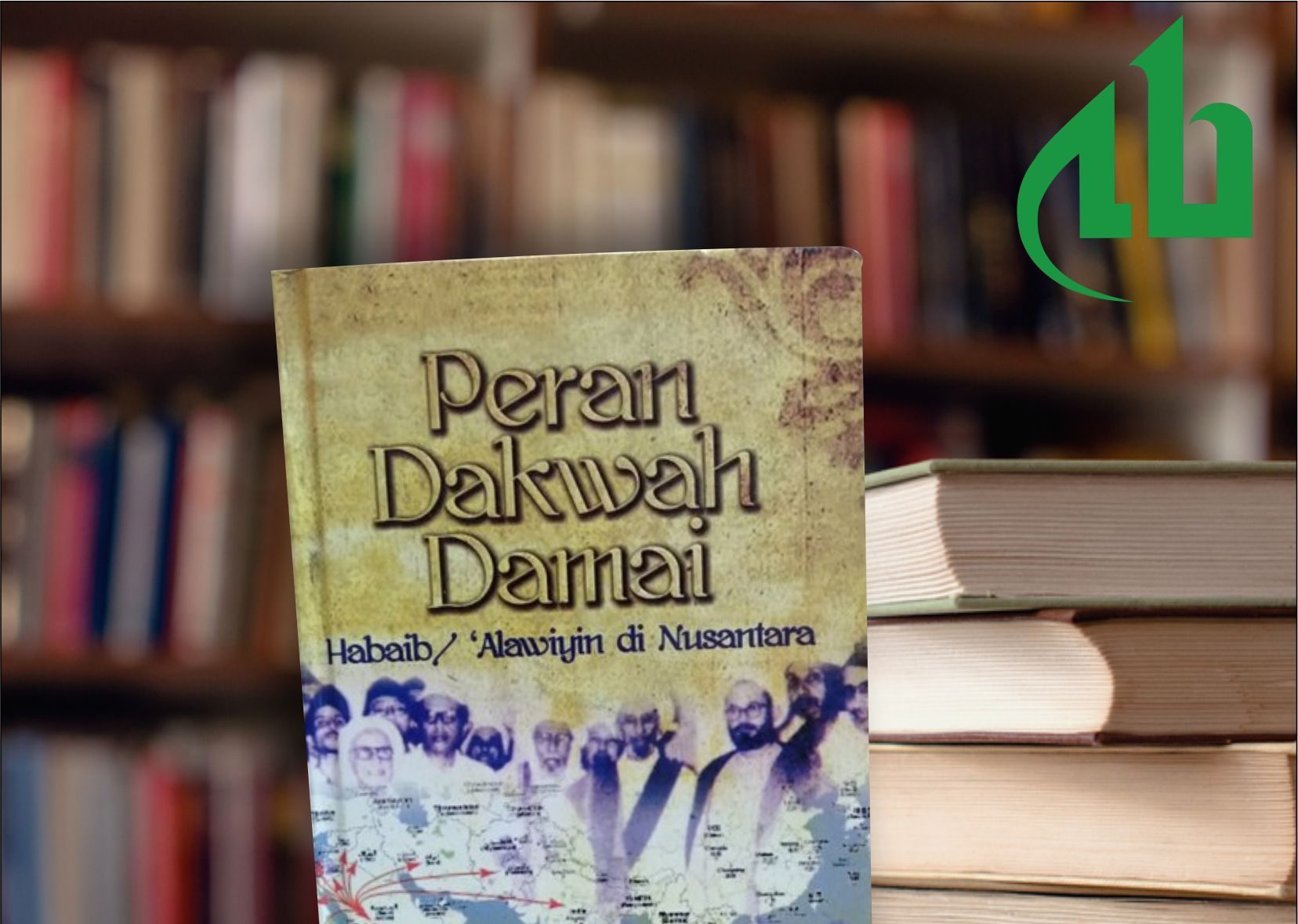
Pertengahan Juli (2012, –red) lalu, ratusan habib berkumpul di Jakarta. Mereka tak sedang menggelar aksi penyisiran menggebrak tempat antimaksiat menjelang puasa. Sebaliknya, mereka justru sedang berdiskusi dalam sebuah seminar internasional tentang cara dakwah yang damai dan toleran, berdasarkan sufisme dan spiritualitas yang mendasari kesadaran beragama masyarakat kita sejak berabad-abad silam.
Tentu saja bukan hanya habaib (jamak kata habib) yang ada. Selain dari Yaman dan Pakistan, seminar juga menghadirkan pakar dari Amerika Serikat, seperti Prof. Engseng Ho (Duke Universty), Dr. Mark Woodward (Arizona State University), dan Ismail Fajri Al-Attas (Michigan State University). Dari dalam negeri, di antaranya hadir Habib Lutfi bin Yahya dan Prof. Azyumardi Azra (UIN Jakarta).
Diskusi ilmiah itu bukan saja penting, juga tepat waktu, khususnya melihat gejala meningkatnya ekstremitas dan intoleransi di tengah umat yang kian mengkhawatirkan belakangan ini. Pasalnya, secara historis, tasawuf dan spiritualitas telah jadi tulang punggung penyebaran Islam yang ramah: tidak saja di Nusantara, tetapi juga di sejumlah wilayah di Asia Tenggara.
Dalam kaitan itu, sejumlah riset tentang masuknya Islam di Asia Tenggara menunjukkan besar peran golongan keturunan Nabi Muhammad asal Hadhramaut (Yaman bagian selatan) yang dikenal dengan sebutan Sayid al-‘Alawiyin atau habaib.
Ditengarai, kaum ‘Alawiyin dengan thariqah ‘Alawiyah-nya, berperan sentral dalam mempromosikan metode dakwah ini sejak awal meluasnya penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-13. Namun, sebelum gelombang ‘Alawiyin itu, sekitar abad ke-13, Indonesia telah mendapatkan penyiaran dakwah berkat masuknya para tokoh sayid (termasuk Wali Songo) ke sejumlah daerah Nusantara. Mereka ini lebih populer daripada gelar-gelar lokal, kemudian bermukim dan beranak-pinak di Nusantara.
Pada abad ke-13, kegiatan islamisasi Nusantara kelihatan lebih nyata ketika bukan hanya pedagang Arab yang merantau ke negeri kita, tetapi juga lebih banyak guru dan dai (juru dakwah) profesional berhasil mengislamkan para penguasa lokal di berbagai penjuru Nusantara.
Mematahkan Pedang
Secara geopolitik, kejatuhan kekhalifahan Baghdad ke tangan Mongol pada 656 (1258 M) menyebabkan kaum sufi makin berperan di dunia Muslim. Secara bertahap, mereka mengembangkan afiliasi dengan kelompok pedagang dan perajin yang turut membentuk masyarakat urban. Hal itu mempercepat proses ekspansi Islam lewat pengembaraan para syeikh, sayid, dan makhdum ke berbagai penjuru dunia.
Jauh sebelum jatuhnya Baghdad pada sekitar tahun 320 H, seorang cucu Nabi Muhammad saw bernama Ahmad bin ‘Isa (aI-Muhajir) hijrah dari Irak ke Hadhramaut untuk menghindari persekusi penguasa Dinasti Abbasiyah di Baghdad.
Belakangan, salah seorang cucu al-Muhajir, yakni Al-Faqih Al-Muqaddam, melakukan upacara pematahan pedang sebagai simbol politik dan sosial-religius penghentian penggunaan senjata. Sebagai gantinya, ia mempromosikan metode dakwah damai dengan pendekatan tasawuf yang disebut sebagai “thariqah ‘Alawiyah” itu (ini koreksi tulisan saya di Kompas, 3 Januari 2012, yang menyebutkan al-Muhajir yang mematahkan pedang). Sejak itu, penekanan pada tasawuf dan metode dakwah damai inilah yang secara turun-temurun mewarnai “mazhab” kaum ‘Alawiyin (berasal dari nama salah seorang kakek al-Faqih al-Muqaddam, yakni Alwi bin Ubaydillah) di mana pun mereka berada, termasuk di Nusantara sampai sekarang.
Dapat disepakati bahwa faktor utama keberhasilan dakwah mereka adalah kemampuan para ulama dari kalangan habaib itu dalam mengemas pesan-pesan Islam secara harmonis dengan budaya lokal yang berakar pada sifat keramahbudayaan tasawuf. Alhasil, dalam waktu relatif singkat, mereka mendapat tempat di hati para elite berbagai pusat kerajaan ataupun masyarakat bawah bangsa-bangsa Asia Tenggara.
Kenyataannya, para raja dan penguasa setempat pun secara sukarela membuka diri terhadap Islam. Tak sedikit tokoh awal dari kalangan Alawiyin migran -yang datang ke Indonesia tanpa membawa istri- kemudian menjadi bagian keluarga beberapa kerajaan di Nusantara, Malaysia, Champa (Kamboja), dan Filipina lewat jalur pernikahan.
Para penduduk Nusantara pun, yang semula sangat menghayati ajaran-ajaran Hindu, segera menyerap dan menghayati aspek-aspek kebatinan (spiritualitas atau tasawuf) Islam ini. Seperti juga yang ditengarai Engseng Ho, bobot sufistik itulah yang menjadikan pesatnya keberhasilan dakwah secara damai tanpa melibatkan penaklukan dan ekspedisi militeristik. Dapat dikatakan, aliran pemikiran dan praktik keagamaan organisasi massa, seperti NU, adalah warisan thariqah Alawiyah ini.
Kini Dapat Tantangan
Sayangnya tradisi pengajaran Islam sufistik dan damai itu kini justru mendapat tantangan dari kaum literalis-radikal atau yang biasa disebut kelompok garis keras. Oleh mereka dakwah damai bahkan dianggap menyimpang. Sikap ekstrem kelompok yang disebut belakangan ini, bila tidak diredam sangat boleh jadi akan makin menyuburkan benih-benih fundamentalisme dan ekstremisme di Indonesia, sebagaimana ia telah merobek-robek kedamaian di Pakistan, Afganistan, dan banyak negara lain di dunia.
Habib Syafiq Basri Assegaf
Dikutip dari buku Peran Dakwah Damai Habaib / ‘Alawiyin di Nusantara













