Tafsir
Tafsir Sufi: Sebuah Prolog
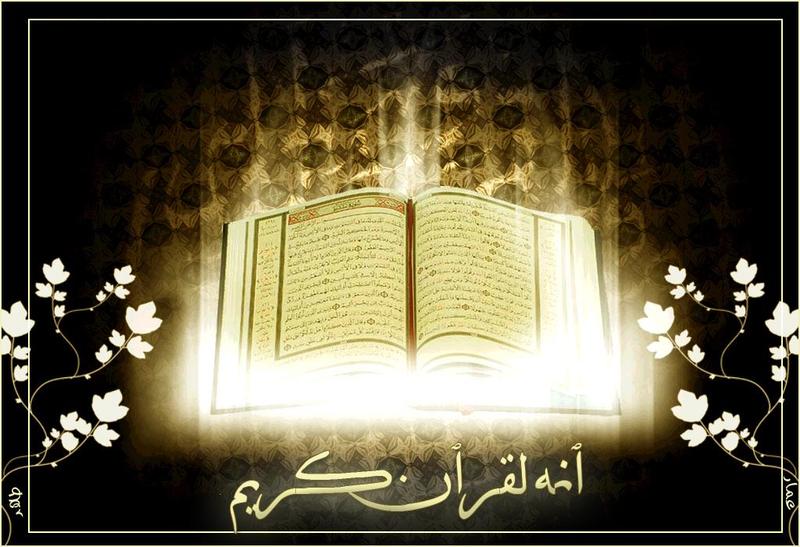
Dalam pandangan kaum sufi, Al-Qur’an adalah Firman Ilahi yang terbuka dan tak terbatas. Tiap-tiap huruf, kata dan kalimat yang terkandung di dalamnya memiliki makna yang bertingkat-tingkat dan berlapis-lapis. Al-Qur’an adalah kumpulan âyât (tunggal, âyah), yakni tanda-tanda yang menggambarkan hakikat yang sesungguhnya.
Kata âyah di dalam Al-Qur’an bisa pula bermakna tanda-tanda yang terdapat di alam penciptaan. Kalau di dalam Al-Qur’an âyah berarti beberapa kalimat yang mempunyai kesatuan maksud sebagai bagian dari surah, maka di alam raya âyah berarti fenomena atau kejadian yang menjadi tanda bagi Sang Pencipta. Dalam surah An-Nahl (16) ayat 89 Allah berfirman: “…”
Dengan demikian, Al-Qur’an berkedudukan sebagai transkripsi alam ciptaan, di mana tiap-tiap huruf dan kalimatnya mengisyaratkan pada kejadian dan kenyataan yang sesungguhnya. Allah berfirman: “Pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang gaib; tiada yang mengetahuinya kecuali Dia… (QS 6: 59).
Sebagaimana tiap ciptaan memiliki sisi tampak dan sisi tak-tampak, huruf-huruf dan kata-kata dalam Al-Qur’an juga memiliki sisi tampak dan sisi tak-tampak. Bahkan, lebih dari itu, dalam sebuah hadis masyhur disebutkan bahwa Al-Qur’an memiliki beberapa lapisan, dan tiap-tiap lapisan mempunyai pintu menuju cakrawala yang tak terbatas. Hal demikian ini dikarenakan Al-Qur’an merupakan representasi tekstual dari lauh mahfûzd yang melambari seluruh penciptaan. Oleh karena itu, para sufi melihat Al-Qur’an sebagai cakrawala yang luas, sebagaimana ilmuwan melihat alam semesta.
Sebagai contoh, dalam pandangan fisika kuantum kita mengenal apa yang disebut dengan medan gaya. Medan ini dapat didefinisikan sebagai struktur tidak terlihat yang menempati ruang angkasa dan kita mengenalinya melalui pengaruhnya.[1] Medan-medan itu, menurut Gary Zukav, “merupakan inti alam semesta. Benda-benda yang kita lihat atau kita amati dalam berbagai percobaan, yakni manifestasi fisik materi sebagai partikel, merupakan efek sekunder dari medan”[2] Kesimpulan ilmiah ini mau tidak mau mendorong para ilmuwan untuk menjauhi cara berpikir materialistik dan parsial yang dominan. Sebaliknya, teori medan memaksa para ilmuwan untuk berpikir tentang sebuah alam yang mengandung berbagai pengaruh yang saling bertemu dan struktur tak terlihat yang saling berhubungan.
Merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur’an itu sendiri, para sufi melihat Al-Qur’an sebagai sebuah semesta makna yang tidak terbatas tetapi saling berhubungan. Medan-medan makna yang terkandung di dalam Al-Qur’an lebih luas daripada medan-medan yang mengisi alam fisik, lantaran Al-Qur’an juga berbicara tentang alam-alam lain di luar alam fisik. Ditopang oleh kekuatan bahasa Arab yang digunakannya, suatu bahasa yang jelas-tegas tetapi juga lentur dan fleksibel, Al-Qur’an siap menyedot semua kemungkinan makna yang dapat dipikirkan oleh manusia. Lebih jauh, Al-Qur’an membuka cakrawala pemahaman dan pengetahuan yang bahkan tak tertampung oleh akal pikiran dan imajinasi manusia.
Untuk menghindari kerancuan dalam menafsirkan Al-Qur’an, seseorang mesti mengikuti pesan Al-Qur’an secara keseluruhan. Dengan kata lain, meskipun menggunakan bahasa yang lentur, Al-Qur’an tetaplah merupakan sebuah kesatuan yang utuh. Memahami Al-Qur’an secara sepenggal-penggal termasuk dalam perkara yang dilarang oleh Al-Qur’an itu sendiri. Allah berfirman: “ Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan) Kami telah menurunkan (azab) kepada orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah). (Yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur’an itu terbagi-bagi.” (QS 15: 90-91).
Prinsip kesatuan makna dan pesan Al-Qur’an ini sebenarnya selaras dengan prinsip kesatuan wujud (wahdah al-wujûd) yang diyakani oleh sebagian besar sufi. Inti prinsip ini adalah hubungan yang mengikatkan segala sesuatu pada Satu Pusat. Segala sesuatu selain Wujud Mutlak tidak lain daripada pantulan dan bayangan-Nya. Tiap-tiap bayangan merupakan Nama yang merepresentasikan Sang Wujud Mutlak.
Manusia tidak bisa mengenal Sang Wujud Mutlak itu tanpa melalui Nama-nama yang tersusun secara bertingkat ini, sedemikian sehingga Nama yang di bawah memahami Nama di atasnya secara bertahap hingga sampai kepada Nama Tertinggi (Al-Ism Al-A’zham). Nama Tertinggi itu hanya dapat dipahami oleh Manusia Sempurna (Al-Insan Al-Kamil), yakni Muhammad Rasulullah saw. Dan Manusia Sempurna hanya dapat dipahami oleh manusia-manusia suci yang dalam Mazhab Syiah dipercayai sebagai Fathimah, Ali bin Abi Thalib, dan sebelas imam keturunan beliau ‘alayhim as-salam.
Atas dasar prinsip itu, untuk memahami Al-Qur’an, para sufi mengajarkan kita untuk berpegang pada makna yang ingin disampaikan Al-Qur’an, dan bukan pada ragam makna yang mungkin dipahami darinya. Di sinilah kita bertemu dengan metode yang disebut sebagai ta’wil. Secara singkat, ta’wil ialah upaya untuk kembali kepada makna asal suatu kata yang digunakan. Bagi para sufi, berpegang pada asal kata dan bukan pada contoh-contoh objektif-empirisnya akan mengantarkan kita pada pemahaman yang tepat.
Sebagai misal, makna asal ‘arsy adalah singgasana yang tidak melulu terbuat dari kayu atau besi. Singgasana sebagai sebuah makna terbebas dari segala bentuk dan rupa. Ia adalah ungkapan tentang kekuasaan, keagungan dan kemegahan. Dalam konteks kemanusiaan, singgasana merupakan tempat duduk raja yang terbuat dari bahan-bahan material, tetapi dalam konteks ketuhanan singgasana adalah sesuatu yang mustahil terbuat dari bahan-bahan material.
Akan tetapi, ta’wil Al-Qur’an merupakan pemberian Allah kepada orang-orang yang berilmu mendalam dan kukuh. Allah berfirman: (QS 3: 7). Jadi, selain dengan cara berpegang pada kata asal, ta’wil yang sebenarnya ada pada hadis-hadis Nabi dan orang-orang suci. Apapun hasil ta’wil yang kita temukan dari Al-Qur’an mesti kita bandingkan dan kita cocokkan dengan hadis-hadis Nabi dan perkataan orang-orang suci. Bila terjadi perbedaan, maka hasil ta’wilyang kita peroleh gugur dan harus diabaikan.
Dengan cara pandang yang demikian, kita dapat menemukan arti penting dari hadis Rasulullah yang menyandingkan Ahlul Bait beliau dengan Al-Qur’an sebagai dua pusaka besar (tsiqlayn atau tsaqalayn) kepada umatnya. Bila kita berpegang kepada keduanya, selamatlah kita dari kesesatan. Sebaliknya, bila kita hanya berpegang kepada salah satunya tanpa selainnya, kita akan tergolong dalam orang-orang yang sesat.
Dalam bukunya yang berjudul Ahl Al-Bayt fi Al-Kitab wa Al-Sunnah, Muhammad Ray Syahri mencatat hadis ini diriwayatkan tidak kurang dari 33 sahabat, antara lain: Umar bin Khaththab, Abdurrahman bin ‘Auf, Abu Ayyub Al-Anshari, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Zaid bin Arqam, Zaid bin Tsabit, Sa’d bin Abi Waqqash, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Abbas dan sebagainya.[3] Selain 33 sahabat ini, Ali Al-Milani mencatat adanya 19tabi’i dan 300 ulama, tokoh dan ahli hadis dari kalangan Ahlussunah yang meriwayatkan hadis ini.[4]
Musa Kazhim

